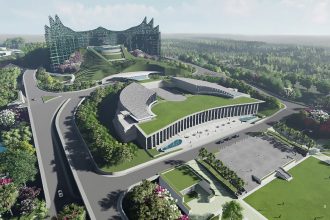Saat upacara perkawinan, biasanya bebantenan untuk mempelai perempuan diletakan terpisah (di bawah banten laki-laki). Bahkan suami dan keluarga dari pihak laki-laki tidak mau makan surudan bantennya. Sang istri harus siap mendapatkan perlakuan yang tidak sejajar oleh keluarga suami. Dalam tata tertib berbahasa misalnya, isteri diharuskan berbahasa Bali alus, bukan hanya kepada keluarga suami namun juga kepada anak-anaknya.
Isteri juga akan dilarang bersembahyang dan mengikuti upacara-upacara di pura keluarga dan pura kawitannya serta dilarang untuk mendoakan roh leluhur dan orang tuanya ketika meninggal nanti. Sedangkan apabila nanti si isteri meninggal, anak-anaknya, suami dan keluarga suaminya tidak akan dibenarkan untuk memikul mayatnya ke kuburan (Sumartika dkk, 2019). Bahkan pada beberapa daerah, sang istri harus rela melayani para ipar dan keluarga suami yang memiliki kasta lebih tinggi.
Walaupun jaman sekarang hal tersebut sudah jarang dilakukan, tapi masih ada beberapa orang yang masih kental kasta-nya menegakkan prinsip tersebut demi menjaga kedudukan kastanya.
Tidak efisiennya implementasi dari Keputusan DPRD Bali pada tahun Tahun 1951 yang menyebabkan PHDI menerbitkan 2 buah larangan Parisada Pusat/X/2002. Bhisama PHDI, dalam pengimplementasianya belum berhasil menghapus istilah kawin turun wangsa dan upakara petiwangi (Sudiana, 2007). Sanksi bagi perkawinan beda kasta masih berlaku dilingkungan pakraman adat oleh masyarakat, maka (MUDP) menerbitkan kembali kemudian sebagai Keputusan MUDP ke III Tahun 2010 memutuskan Upakara tersebut sudah dihilangkan dalam upakara perkawinan.
MUDP memahami bahwa upakara dalam perkawinan berlainan wangsa sangat bertentangan dengan UU Nasional dan HAM bagi sebagian besar dapat menimbulkan gejolak ketidaksetaraan status perempuan dalam tingkatan kekerabatan, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian (Anonim, 2011).
Konsep HAM tidak membenarkan adanya beda kasta dan ketidaksejajaran hak antara suami-isteri dalam perkawinan, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, setiap warga negara bersamaan statusnya dan wajib segala hukum dijungjung tinggi dan tidak ada kecualinya dalam pemerintahan.
Terdapat pengingkaran hak-hak perempuan Bali dalam hidup dan kehidupannya, hak untuk memiliki kekerabatan, penyetaraan hak dan keadilan, hak aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan taraf dan wangsa manusia. Karena dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Kurangnya pendidikan menyebabkan perempuan Bali sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena mereka tidak berani melapor. Ketidak beranian tersebut menyebabkan tindakan kekerasan yang terus berulag hingga menyebabkan luka fisik dan juga batin. Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali yang di dalamnya mengubah norma-norma hukum adat Bali terkait hak-hak perempuan cukup progresif memberi arah bagi perkembangan hukum adat Bali di masa depan, namun masih perlu disosialisasikan dan dinternalisasikan di masyarakat, baik dilingkungan praktisi hukum (hakim, notaris, pengacara), lingkungan tokoh-tokoh adat dan agama, serta masyarakat luas. Masih panjang jalan menuju kondisi di mana jiwa Keputusan Pesamuan tersebut benar-benar menjadi pola perilaku nyata masyarakat Bali.