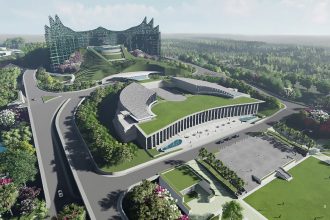Kemauan politik (Political Will) pemerintah telah tercermin dari penerbitan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tetapi tingkat realisasinya masih jauh dari harapan, seperti terabaikannya hak-hak petani, janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan perbaikan ekonomi dalam kerangka reforma agraria tidak kunjung diterima petani. Tidak sinkronnya IGT (Informasi Geospasial Tematik) dari setiap kementerian telah menjadi sumber permasalahan utama dari konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Persoalan konflik agraria tidak hanya sekedar usaha perluasan lahan atau penerbitan izin baru perkebunan yang merampas hak-hak masyarakat atas tanah mereka, melainkan juga buruknya sistem birokrasi pertanahan dimasa lalu yang menyebabkan tumpang tindihnya hak masyarakat atas tanah dengan pihak swasta maupun perusahaan milik Negara yang telah berlangsung sejak lama. Hal ini terus terulang hingga saat ini, dimana pemerintah tidak melakukan upaya progresif untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan rezim lama, dengan terus membiarkan perusahaan perkebunan yang sudah jelas menyalahi prosedur atau sudah habis masa izinnya tetapi masih bebas beroperasi di masa pemerintahan saat ini.
Ada banyak organisasi masyarakat yang telah memperjuangan hak penguasaan tanah, tetapi seringkali mereka selalu kalah ditangan para pemodal besar. Negara seharusnya mampu bertindak sebagai perisai pelindung rakyat, terutama kepada kalangan miskin. Namun negara kerap kali memberikan izin usaha seperti HGU (Hak Guna Usaha), HBD (Hak Guna Bangunan), ijin lokasi usaha perkebunan dan pertambangan secara sepihak tanpa adanya upaya dialog dengan penduduk sekitar. Negara telah salah kaprah mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan, padahal berdasarkan Pasal 2 UUPA dan penjelasannya, UUPA mengartikan konsep “dikuasai“ oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan negara mempunyai suatu hak untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir adalah faktor elit penguasa yang terpisah dari elit bisnis. Di Indonesia sudah menjadi rahasia umum kalau sektor strategis seperti ekstraktif, energi dan infrastruktur kerap menjadi ladang korupsi oleh elit politik, khususnya dalam sektor pertambangan baru bara, dimana Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pasokan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Peran One Map Policy dalam Upaya Percepatan Reforma Agraria
Menurut Presiden Jokowi, saat ini terdapat 77,3 juta hektare lahan atau hampir 40 persen wilayah Indonesia mengalami tumpang tindih lahan. Hal inilah yang kemudian menjadi akar permasalahan dari meningkatnya konflik agraria di Indonesia. Program OMP pertama kali digagas pada saat masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu terjadi ketidaksinkronan antara data geospasial UKP4 dengan data geospasial dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, hal ini tentunya menyebabkan tumpang tindih formasi peta yang dimiliki oleh setiap kementerian. Pemerintah pada waktu itu (2010) menugaskan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membuat OMP untuk menyatukan seluruh IGT dari berbagai lintas sektor. Konflik agraria seringkali disebabkan oleh ketidakselarasan administrasi pertanahan, tidak hanya itu, pelayanan administrasi pertanahan belum sepenuhnya mampu menyajikan data secara valid dan akurat, contohnya adalah suatu kawasan diklaim sebagai kawasan hutan, namun fakta sebenarnya menunjukkan bahwa kawasan tersebut telah menjadi pemukiman.
Dalam rangka mendorong realisasi kebijakan OMP, pada 1 Februari tahun 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). OMP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan. Penerapan OMP akan berguna bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam berbagi data dan Informasi Geospasial sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh Kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan perijinan maupun kebijakan.