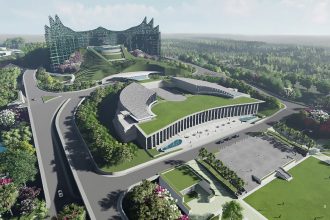Karena itu karakteristik pertama sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara (Effendi, 2005). Dengan sistem presidensial di Indonesia maka seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada pihak yang mendominasi. Namun dalam praktiknya demokrasi kita yang tak lepas dari campur tangan para oligarki.
Itu sebabnya kita bisa melihat persentase para calon pemimpin yang kebanyakan memiliki latar belakang politik, militer atau kalangan pengusaha yang menepati jajaran teratas piramida perekonomian nasional. Keberadaan oligarki dalam pemerintahan akan mengganggu pelaksanaan demokrasi.
Tidak berhenti sampai disitu, keberadaan oposisi juga seakan-akan dibungkam. Contohnya keputusan Jokowi menggandeng Prabowo yang kini ikut menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju. Ini memperjelas bahwa keberadaan oposisi mulai digerogoti untuk mengurangi pergolakan internal dalam pemerintahan. Hal tersebut justru malah mengkhawatirkan.
Bila oposisi dilemahkan, maka checks and balances terhadap kinerja pemerintah akan melunak. Padahal keberadaaan oposisi sendiri merupakan salah satu wujud adanya demokrasi. Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan.
Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi (Sunarto, 2016).
Selain itu juga arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah (Noor, 2016).
Demokrasi Sebatas Euforia?
Pesta demokrasi yang kini kita rasakan hanyalah euforia semu belaka. Realitas yang kita sebut dengan pesta demokrasi di Indonesia bukan diperuntukkan kepada warga negara yang antusias dalam menggunakan hak pilih terhadap calon-calon pemimpin berpotensial.
Melainkan pesta dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang memakan biaya tinggi seolah melelang harga dari hak suara sebagai warga negara. Sebagaimana pemaparan oleh Direktur Jenderal Anggaran Askolani, pemilu tahun 2017 hingga 2019 dianggarkan mencapai Rp25,59 triliun (Kemenkeu, 2019).
Merujuk dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam satu kali pelaksanaan pemilu saja begitu besar dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan suara dari rakyat Indonesia. Hal ini seakan-akan menempatkan pemilu sebagai ajang menghambur-hamburkan uang demi menyokong citra baik mereka dimata rakyat Indonesia.
Belum lagi adanya fenomena money politics yang masih ditemukan dalam pemilu 2019 kemarin. Politik uang merupakan kontradiksi dari semangat demokrasi. Dimana ukuran integritas tidak lagi dibutuhkan, karena segalanya hanya diukurberdasarkan gelimang harta yang digelontorkan (Prasada, Alfiyansyah, Febrian & Dewi, 2020).
Pemberitaan di media massa terkait money politics dalam penyelenggaraan kampanye terus bertambah setiap harinya ketika musim pemilihan umum tiba. Pemberitaan kasus tersebut tergolong sering dan berulang kali, sampai satu mingguan lebih masih tetap diberitakan.