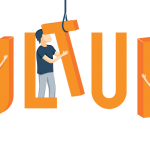Teringat di pikiran kita mengenai pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Seketika gejolak masyarakat Bumi Cenderawasih menjadi meninggi, tidak hanya di Papua sebagai daerah asalnya, namun hampir di seluruh wilayah Indonesia terutama kota-kota di Pulau Jawa sebagai kota tujuan “Anak Papua” untuk menempuh pendidikan. Tragedi rasialisme 2019 itu mengingatkan penulis pada hal-hal berbau rasial terhadap warga negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa yang sebenarnya masih terjadi (bahkan) hingga saat ini.
Mungkin bila kita membaca buku atau menonton film besutan Ernest Prakasa berjudul “Ngenest”, dapat tergambar bentuk diskriminasi pada era pra-reformasi. Bagaimana ungkapan “Eh, ada Cina” atau “Sipit” merupakan ungkapan sehari-hari yang bahkan menjadi budaya. Bagi sebagian besar penontonnya, hal tersebut terlihat seperti guyonan tidak serius, hanya sebuah film komedi untuk menghibur masyarakat. Namun bagi penulis yang pada tahun sekitar 2012 pernah berjalan kaki sepulang sekolah dan diteriaki “Hei Kamu Cina” dengan nada mengejek oleh tiga orang tak dikenal, tentunya akan memiliki arti lain yang cukup mengena.
Walaupun memang itu mungkin dapat dianggap sebagai suatu candaan, namun jika itu dilakukan secara spontan oleh orang-orang tak dikenal, apakah hal itu masih dapat dikatakan bercanda?
Diskriminasi Ras Masih Banyak Terjadi
Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi yang ada bahkan telah menjadi diskriminasi sistemik yang masuk dalam ranah hukum dan pemerintahan. Diskriminasi sistemik itu secara garis besar terangkum dalam Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Larangan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang disahkan oleh “The Smiling General”. Tercatat oleh Ali Mustajab (2015) dalam jurnal berjudul “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia”, bahwa rezim Orde Baru memberikan sejumlah batasan hak sipil pada WNI keturunan Tionghoa seperti sulitnya akses untuk berprofesi sebagai birokrat (Aparatur Sipil Negara/ASN), militer, bahkan masuk perguruan tinggi (negeri).
Selain hak-hak yang bersifat sipil, adapula hak-hak lain yang dilarang, seperti larangan penggunaan Bahasa Mandarin, pendirian sekolah-sekolah Tionghoa (berbahasa Mandarin) dan perayaan tahun baru Imlek secara umum. Rasanya, merupakan suatu dosa besar terlahir sebagai seorang Tionghoa.
Tahun 1998 terasa sebagai puncak dari semua perlakuan diskriminasi tersebut, seperti yang dicatat oleh Dewi Rahmayuni dan Helmi Hidayat (2020) bahwa etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk kerusuhan Mei 1998 dengan dalih bahwa kelompok etnik inilah yang menjadi biang komunisme di Indonesia dan tidak memiliki rasa nasionalisme terhadap ibu pertiwi.