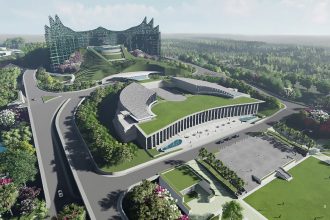- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/ tentang sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) oleh KPU RI terhadap Partai Prima telah mengundang perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Beberapa kritik yang muncul di antaranya terkait dengan kompetensi hakim dalam kasus ini dan dugaan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/ mengenai sengketa Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU RI terhadap Partai Prima telah menjadi polemik nasional. Putusan ini mendorong para ahli hukum berkomentar keras dengan bahasa provokatif seperti, “kita lawan habi-habisan,” “ada yang aneh di negeri ini,” “putusan yang cacat hukum,” “putusan mencari sensasi,” hingga pernyataan “hakim layak dipecat.” Masih banyak lagi komentar bernada ketus, meledek, dan merendahkan martabat putusan pengadilan dan hakim PN Jakarta Pusat.
Secara umum, komentar-komentar tersebut merupakan hal biasa dan wajar. Kalangan sipil, seperti pemuda warung kopi, mahasiswa hukum, sampai ahli hukum, memiliki hak dalam berkomentar. Hal ini juga terasa wajar dengan huru-hara dan implikasi Putusan PN Jakarta Pusat ini. Bagaimana tidak, perintah penundaan pemilu menguncang tata hukum Indonesia. Hampir seluruh berita di internet berisi nada ancaman, penolakan, dan secara terang benderang menganggap hakim tidak layak dan tidak paham perkara ini.
Penulis teringat huru-hara ini pernah terjadi hampir 5 dekade lalu, tepatnya pada Senin, 8 Agustus 1983 ketika ‘kehormatan’ wanita dianalogikan hakim sebagai barang. Pada prinsipnya, tidak ada satupun teks undang-undang yang dapat dijadikan dasar rujukan ilmiah dalam argumentasi ini. Bismar Siregar adalah hakim yang berani melakukan kegilaan itu dan mungkin hanya dia yang berfikir demikian. Putusan seperti ini secara pasti dan menyakinkan membuat huru-hara yang luar biasa baik di kalangan rakyat maupun ahli hukum.
Beberapa aktivis bantuan hukum seperti Wayan Sudirta, Todung Mulya Lubis, Abdul Rahman Saleh, dan Teguh Samudera memberikan tanggapan positif terhadap putusan tersebut. Sementara itu, pengacara Ibukota Rusdi Nurima menyoroti bahaya batasan penafsiran undang-undang dan potensi lahirnya kejahatan baru. Ketua Muda Pidana MA, Adi Andojo Soetjipto, sangat kritis terhadap putusan tersebut dan menyebutnya terlalu jauh dalam menafsirkan aturan main serta tidak memperhitungkan dampaknya terhadap kepastian hukum.
Kasus PN Jakarta Pusat dan pernyataan hakim pada 1983 menunjukkan pentingnya pemahaman kewenangan hakim dalam penafsiran dan penemuan hukum. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk menjaga kelangsungan hukum dan keadilan. Penerapan undang-undang pada peristiwa konkret melibatkan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang. Penafsiran hukum merupakan kegiatan mutlak terbuka oleh hakim, sejak hukum dikonsepkan sebagai teks undang-undang.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan kewajiban hakim memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, hakim perlu mencari atau menciptakan hukum baru untuk memutuskan kasus. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst terkait penundaan Pemilu 2024, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penafsiran hukum adalah kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan oleh hakim, sejak hukum dikonsepkan sebagai teks undang-undang.
Terlepas dari pro dan kontra terhadap Putusan PN Jakarta Pusat, pasti terdapat argumentasi dari sudut pandang undang-undang. Ini bukan merupakan kekeliruan, tetapi hakim pasti lebih tahu apakah putusanya merupakan tindakan yang keliru. Penulis yakin Putusan PN Jakarta Pusat telah melalui ikhtiar keilmuan yang mendalam oleh hakim. Tidak mungkin hakim tanpa sadar membuat suatu putusan yang orang awam menyebut putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang, bukan kompetensi pengadilan maupun tidak memiliki dasar hukum.