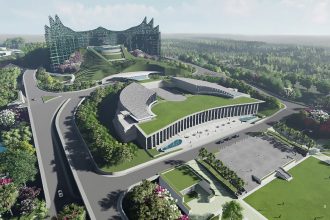Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pertama struktur, kedua substansi (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have) dan yang ketiga adalah budaya hukum. Dari semua factor itu orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.[1]
Hukum sebagai a tool of engineering adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah system social. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu social engineering dan social planning.[2] Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (a tool of social engineering).[3]
Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (restitutio in integrum=kembali ke keadaan semula).[4] Di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum.[5]
Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban (rust en orde) serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial (tool of social enginering) guna menuju social welfare. Roscoe Pond sebagaimana dikutip Ade Maman Suherman menegaskan bahwa hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan antarwarga masyarakat.[6] Adanya unsur interaksi menunjukkan bahwa eksistensi hukum hanya ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” seperti ungkapan Tulieus Cicero (106-45 SM) seorang filsuf Romawi dengan teorinya “ubi societes ibi ius” yang menembus ruang dan waktu. Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia.[7] Teori Cicero tersebut di atas didukung pula oleh Van Apeldorn dengan teorinya bahwa, “hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana”.[8] Dengan demikian, menurut Von Savigny dalam Satjipto Rahardjo, “es ist und wird mit dem voelke”, hukum akan terus menerus dibicarakan selama kehidupan manusia masih ada.[9]
Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undangundang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosa kata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis. Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu language game, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda.[10]
Portalis sebagaimana dikonstantir oleh Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru.[11]
Sejalan dengan pendapat Portalis tersebut, Bagir Manan dalam Ridwan HR menyatakan bahwa undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (moment opname) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit.[12] Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat.[13]
Jika suatu materi muatan peraturan perundang-undangan pure berasal dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas praesumptio iuris et de iure, bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang-undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi tersebut.[14]
Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peratuaran yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingankepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.[15]
Hukum merupakan wujud dari produk sistem politik dan berguna untuk kepentingan pengendalian sosial dalam suatu sistem sosial. Di sini hukum akan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keserasian hubungan masyarakat dalam proses interaksi sosial dengan kelompok solidaritas sosial lainnya. Menurut Weber hukum yang rasional dan formil merupakan dasar bagi suatu negara modern yang didasarkan pada hubungan fungsional (solidaritas mekanis) dengan spesifikasi pembagian tugas berdasarkan prosedur administrasi. Dalam rangka penegakan hokum, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun hasil meratifikasi hukum internasional. Di samping secara positivisme dalam penegakan hukumnya, maka pemerintah juga menggiatkan peranan dari pranatapranata adat atau hukum adat setempat.[16]
Sejak awal pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelamaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilitas interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial.[17] Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.[18] Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.[19]
Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungasinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (malaise) atau kekurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.[20]