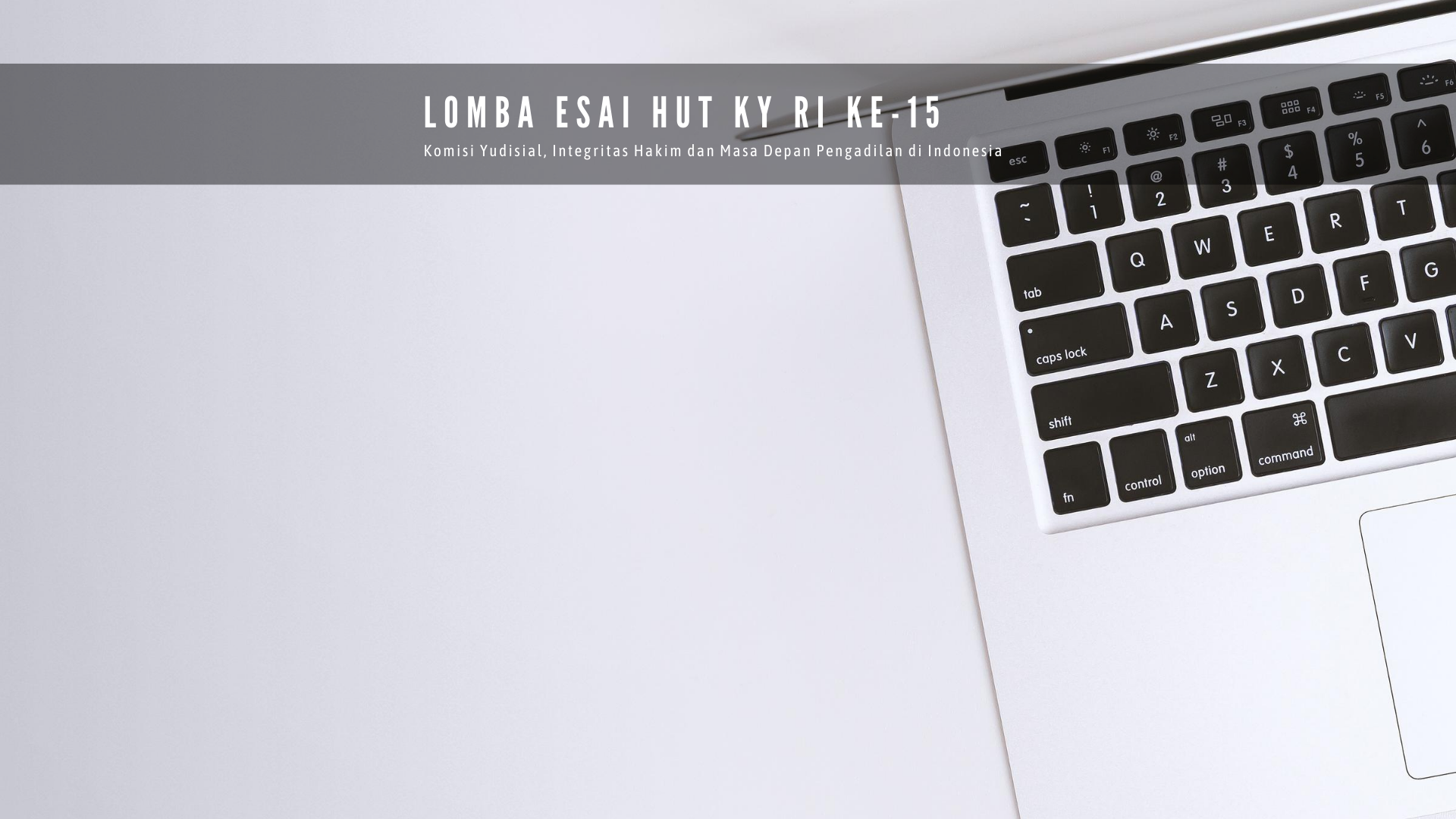Pada sisi lain, pemenuhan hak atas keadilan harus diberikan terutama kepada korban. Melihat hal tersebut, betapa beratnya hakim dalam memberikan putusan untuk melepaskan diri dari konflik kepentingan demi memberikan keadilan substansial proposional.
Ketimpangan Akses Keadilan
Korupsi bukan lah perkara yang ringan dan mudah untuk diatasi. Budaya koruptif menjadi salah satu bagian tingginya angka korupsi di negeri ini. Seorang ilmuwan politik Amerika Serikat Samuel Phillips Huntington pernah mengemukakan bahwa korupsi menjadi penyakit demokrasi dan modernitas. Begitu buruknya korupsi seakan menjadi sebuah benalu jika tidak diberantas hingga ke akar-akarnya.
Bagi sebagian pegiat anti korupsi, upaya menghilangkan budaya koruptif menjadi agenda penting dalam menyongsong Indonesia bersih dari koruptor. Namun, upaya yang dilakukan seakan harus ditempuh dengan jalan yang begitu terjal. Tidak hanya teror ancaman pembunuhan yang siap menghadang setiap saat namun kurangnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga perilaku tidak koruptif juga turut menjadi bagian.
Antara pegiat anti korupsi dan koruptor ibarat seorang petinju amatir yang menantang petinju professional. Jika diadu di dalam ring tinju, petinju amatir akan babak belur. Koruptor akan selalu mendapat akses dengan melakukan banyak upaya agar selalu aman dari jeratan hukum, salah satunya adalah suap. Berbeda jika berada di posisi menjadi pegiat anti korupsi yang rentan terjadi kriminalisasi atau ancaman teror. Menjadi korban seakan sulit mendapatkan akses dalam pemenuhan keadilan. Seperti kisah penyerangan Novel yang pengungkapannya begitu lama.
Adapun koruptor yang berhasil ditangkap dan kemudian divonis ringan menjadikan potret ketidak seriusan dalam pemberantasan korupsi. Jika hukuman para koruptor saja masih tergolong ringan, pemberian efek jera tidak akan pernah tercapai. Apalagi terdapat beberapa hakim yang terperosok dalam pusaran korupsi, seakan menjadikan kewibawaan hakim menjadi menurun. Tidak hanya itu, indeks kepercayaan publik terhadap peradilan pun akan ikut turun. Jika kepercayaan masyarakat pencari keadilan saja sudah tidak bergairah untuk meletakan peradilan dalam menyelesaikan persoalan maka besar kemungkinan tatanan demokrasi akan terkikis.
Performa Komisi Yudisial Semakin Turun
Banyaknya deretan hakim yang terjerat kasus korupsi menunjukan potret kusam wajah peradilan di negeri ini. Lemahnya hakim dalam menjaga kewibawaan dan kehormatannya sebagai penegak hukum seakan memberi sinyal merah lembaga penjaga etika hakim. ICW mencatat ada 20 hakim yang terjerat kasus Korupsi dari tahun 2012 hingga 2019. Tidak hanya terjun kedalam kasus korupsi namun banyak juga Hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku kehakiman (KEPPH). Merosotnya kualitas etika hakim juga menjadi sorotan sebagian lembaga survei untuk menempatkan peradilan menjadi bagian dari lembaga yang korup.
Pada satu sisi, lembaga yang ditugaskan secara konstitusional untuk menjaga marwah kehakiman tidak begitu bergairah. Padahal, sebagian masyarakat menaruh harapan kepada lembaga tersebut untuk menjaga integritas hakim agar selalu berpijak pada norma baik dalam penegakan hukum maupun dalam berperilaku.
Komisi Yudisial seakan menjadi supporting organ bagi Mahkamah Agung dalam pengawasan kehakiman. Sifatnya yang preventif seolah menjadikan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang semu. Jika dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial selain berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung juga mempunyai kewenangan dalam menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal tersebut tidak begitu saja muncul untuk memberikan legitimasi konstitusional kepada Komisi Yudisial namun sebagai bagian dari staat fundamental norm atau yang dikenal menurut Hans Nawiansky sebagai norma dasar sebuah negara yakni Pancasila jika konteksnya adalah Negara Indonesia.