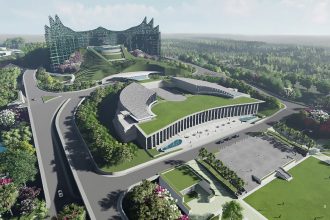Berdasarkan uraian di atas terlihat hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi.
Masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan
“Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum” Adagium tersebut bermula dari pemikiran Profesor Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat dari sebuah negara. Adagium ini membantu kita untuk memahami bahwa saat hukum dibentuk atau tidak dibentuk, ditegakkan maupun tidak ditegakkan semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan manusia. Mengorbankan manusia demi hukum adalah sebuah penyimpangan terhadap hukum itu sendiri.
Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan sejatinya tidak terletak di dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdapat dalam perspektif masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan seharusnya tidak diabaikan, karena hal tersebutlah yang menentukan substansi hukum.
Dalam realitasnya jika kita melihat UU Cipta Kerja, menurut Kerja Ketua Pukat UGM Oce Madril menyebut bahwa proses pembentukan RUU Cipta Kerja berlangsung sangat cepat, tertutup, dan minim partisipasi publik. Secara substansi, UU Cipta Kerja ini mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi. Amnesty International Indonesia juga menilai bahwa UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR sangat tidak progresif. Sebaliknya, banyak ketentuan dalam UU tersebut yang melanggar prinsip non-retrogesi sehingga membawa kemunduran dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat.
Selanjutnya, dalam UU Minerba, pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi menyatakan, dengan adanya pengesahan revisi UU Minerba dinilai cacat dalam proses pembentukannya, baik dari aspek formalitas maupun ditinjau dari segi substansinya. Sedangkan secara substansi terdapat sejumlah pengaturan yang dinilai bermasalah. Hal yang sama disampaikan oleh Budi Santoso selaku Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) yang menilai UU Minerba yang baru disahkan justru tidak membawa angin segar dalam tata kelola pertambangan di Indonesia.
Kondisi hukum di Indonesia belakangan ini menggambarkan apa yang disebut legal gap. Legal gap terjadi ketika adanya kesenjangan atau pertentangan antara hukum positif formal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living law). Dalam bentuk lebih lanjut, legal gap ini dapat memunculkan konflik hukum (legal conflict). Kesenjangan hukum muncul seiring dengan lahirnya peradaban bangsa dan negara yang menyeragamkan hukum hanya sebatas apa yang disahkan oleh badan khusus dalam hierarki negara yang berwenang membukukan hukum.