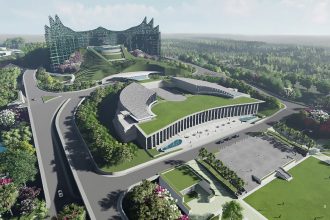Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik agraria merupakan konflik yang tak kunjung tuntas. Meskipun telah mengalami pergantian jabatan, namun tak ada pemimpin yang benar-benar bisa memecahkan. Sejak hadirnya sistem kolonial, tata kelola agraria menjadi ekstraktif dan berpijak pada pasar internasional yang di wujudkan dengan adanya usaha perkebunan. Menurut sejarah, banyaknya perkebunan tersebut tidak hanya melahirkan ketimpangan kepemilikan tanah, tetapi juga demoralisasi sosial.
Berdasarkan data yang bersumber dari Jatama (Jaringan Tambang) dan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), pada tahun 2010 saja di Indonesia sudah terjadi 106 konflik agraria yang melibatkan 517.159 KK dalam konflik tersebut. Jumlah tersebut tentu tidak dapat dikatakan sedikit dan dapat dipastikan meresahkan masyarakat sekitar serta sengketa yang paling banyak terjadi dengan melibatkan perkebunan besar.
Sedangkan di Jember sendiri kurang lebih terdapat 11 konflik tanah yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan. Misalnya pada kasus yang terjadi di beberapa desa seperti Desa Curahnongko (364 hektare) antara masyarakat dengan PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara). Jenggawah (3.274 hektare) antara masyarakat dengan PTPN. Ketajek (1.188 hektare dengan TNI), Karangbaru (90 hektare), Nogosari (388 hektare), Baban (450 hektare). Mandigu (800 hektare) antara masyarakat dengan PERHUTANI, serta di beberapa tempat lainnya antara lain di Desa Curahtakir, Sumberbaru dan Mangaran.
Selaras dengan perkembangan pembangunan di berbagai aspek yang makin hari kian meningkat, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak kecil pada peningkatan kebutuhan akan tanah. Hal tersebut memiliki arti bahwa dalam keterbatasan lahan, pemerintah di tuntut untuk bijak dalam penataan ruang. Sehingga perlu kajian kritis akan skema tata ruang. Khususnya di Kabupaten Jember dengan maraknya kasus tumpang tindih penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).