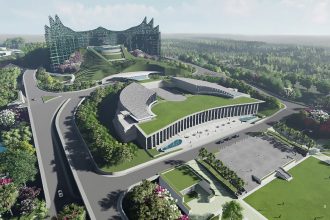Salah satu isu hukum yang paling hangat diperbincangkan sepanjang tahun 2020 adalah tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Ombinus Law secara sederhana dapat diartikan sebagai satu teknik pembuatan undang-undang yang dapat merubah banyak undang-undang (suriadinata, 2019).
UU Cipta Kerja pada kahikatnya dibuat dengan tujuan mulia yaitu untuk memajukan perekonomian Indonesia lewat pembentukan iklim investasi yang sehat. Seperti yang kita ketahui bersama, birokrasi perizinan di Indonesia sangatlah berbelit-belit sehingga menyulitkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu UU Cipta Kerja hadir untuk menjawab masalah tersebut.
Namun, pembentukan UU sapu jagad ini menuai banyak polemik dan penolakan. Masyakat menilai bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil dan materil. Dari segi formil, proses pembuatan UU Cipta Kerja ini menyalahi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UUD 1945. Pasalnya dalam pembuatannya, UU ini minim partisipasi masyarakat dan terkesan terburu-buru, tertutup serta tidak transparan. Dari segi materil, pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini dinilai banyak masalah dan berpotensi merugikan buruh/pekerja, lingkungan, masyarakat adat maupun mengabaikan HAM (Mahendra, 2020).
Tulisan ini akan fokus membahas klaster ketenagakerjaan. Pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dinilai mengancam hak-hak asasi para buruh.
Pembahasan
Dalam proses perumusan hingga pengesahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 November 2020 (detik.com, 2020), UU ini telah mendapat banyak penolakan. Demo penolakan UU ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Sejumlah lembaga dan pegiat aktivis menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI setelah pengesahan UU ini.
Pihak yang paling lantang dan masif menyerukan penolakan adalah kaum buruh atau pekerja. Mereka merupakan pihak yang merasa paling dirugikan akan UU ini. Mereka menilai UU ini abai terhadap hak buruh serta tidak dapat diterapkan karena masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.
Pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja hanya mengedepankan keuntungan serta kepentingan para pebisnis. Sebaliknya, pasal-pasalnya abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak bagi para pekerja, dan hak pekerja perempuan.
Secara umum, poin-poin yang menjadi permasalahan dalam UU Cipta Kerja adalah hak atas upah minimum, hak atas status pekerjaan, batasan terhadap jam kerja, waktu istirahat dan libur serta pengaturan tenaga kerja asing. Pertama, Pasal 88C ayat (2) UU Cipta kerja menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Penggunaan frasa “dapat” menimbulkan multitafsir yang dapat mengandung makna opsional yang berarti gubernur bisa boleh tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Jelas merugikan buruh apabila gubernur tidak menetapkan UMK karena pengaturannya bukan kewajiban sehingga bisa jadi berakibat upah buruh menjadi murah. UU ini menghapus Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 sehingga upah minimum berdasarkan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota dihilangkan.
Kedua, UU Cipta Kerja menghilangkan batas waktu kontrak terhadap PKWT yang terdapat didalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003, menggantinya dalam perjanjian kerja. Akibatnya, pengusaha bisa saja sewenang-wenang dalam membuat perjanjian kerja dan terus mengkontrak PKWT tanpa memberikan hak untuk menjadi karyawan tetap meski telah melewati batas waktu kontrak.