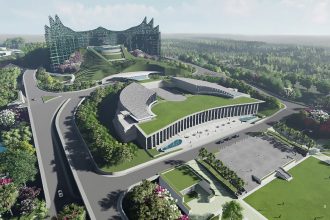Sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008, sistem Pemilu DPR/DPRD 2009 masih sistem proporsional semiterbuka. Artinya, sistem ini masih punya sifat sistem proporsional tertutup. Namun, pada Pemilu DPR/DPRD 2014, tingkat partai politik menyetorkan caleg perempuan nomor urut 1 pada daftar caleg dan tiap dapil menurun drastis.
Penyebabnya adalah UU 8/2012 sejak awal disahkan menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Berdasarkan Putusan MK 22-24/PUU-VI/2008, Pasal 214 UU 10/2008 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penentuan caleg terpilih hanya berdasarkan suara terbanyak, sehingga tidak lagi menyertakan syarat perolehan suara yang mempertimbangkan harga kursi. Hal ini cukup mereduksi keterwakilan perempuan dalam penentuan caleg tersebut.
Selain itu, Putusan MK di atas yang menyatakan Pasal 214 UU 10/2008 tidak berlaku berakibat bahwa tidak ada lagi sistem zipper (penentuan nomor urut) bagi caleg. Seluruh suara sah yang masuk ke dalam parpol tertentu akan dibagi diantara para caleg berdasarkan jumlah suara yang langsung diterima oleh caleg tersebut.
Padahal, pada tataran teoritiknya dalam negara hukum (rechtstaat) terutama di Indonesia, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menetapkan caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak (secara kuantitas) akan menimbulkan dampak signifikan bagi jalannya mekanisme demokrasi di Indonesia.
Titik sentral Putusan MK di atas terhadap affirmative action dalam UU 10/2008 adalah ketidakpunyaan arti atas ketentuan affirmative action. Hal ini mencerminkan bahwa salah satu tujuan pemilu yaitu menyertakan keterlibatan 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam parlemen sebagai respon kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum dapat diwujudkan.
Seharusnya, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dapat direspon. Hal yang paling utama adalah merealisasikan supaya kebijakan khusus yang bersifat sementara dalam rangka menciptakan representasi keterwakilan perempuan guna mewujudkan negara hukum demokratis.
Budaya Patriarki yang Telah Membumi
Sistem pemilu itu bertambah buruk dengan keadaan masyarakat yang masih patriarkis. Meskipun nantinya partai politik sudah menghadirkan perempuan lebih dari 30% dalam pencalonan zipper sistem proporsional terbuka, tidak ada jaminan masyarakat sebagai pemilih dapat ramah terhadap perempuan. Konsekuensinya, keterpilihan perempuan minimal 30% di DPR saja belum pernah tercapai.
Penelitian International Foundation for Electoral Systems (IFES) 2010 menjelaskan persepsi masyarakat Indonesia terhadap kandidat perwakilan perempuan. Dari semua pemilih yang akan memilih perempuan calon, ada perbedaan pertimbangan. 35% memilih berdasarkan kecerdasan (intelligence), 26% memilih berdasar pengetahuan status calon yang bersih dari korupsi (lack of corruption), 20% memilih berdasar pengalaman berpolitik (experiences in politics).
Dari keadaan dan pengalaman tersebut, selain perlu penyesuaian dengan pilihan sistem porporsional yang lebih relevan, dibutuhkan dua pendekatan untuk mengoptimalkan zipper system keterwakilan perempuan. Pertama, kedisiplinan partai politik terhadap komitmen kuota gender dengan zipper system. Kedua, penyadaran masyarakat untuk memilih perempuan caleg dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR supaya dengan terpenuhinya keterwakilan tersebut. Pengambilan keputusan politik akan lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, akan menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.